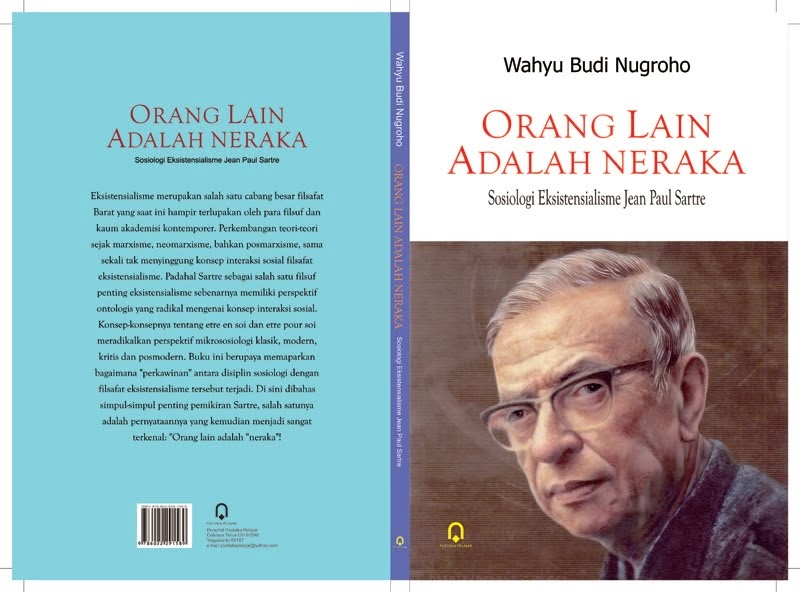Menyoal
Fantasi dan Emansipasi dalam “Foodgasm”
Wahyu Budi Nugroho
Sosiologi Universitas Udayana
dimuat di Jurnal Widya Sosiopolitika Vol.6/No.2, Sept 2015
Abstract
This study pursues to seek the present exaggerated foodgasm phenomena with its social
implications. Straightforward, foodgasm
can be described as; “delightful sensation during eating”. The sensations not
only exist in the “flavour” aspect or human sense of taste, but also visual
aspect. In this case, fantasy is a crucial matter that has a vital role.
Furthermore, this study pursues to formulate some emancipation
alternatives of the fantasy, such as, from Jean Baudrillard’s “seduction”
perspective, Roland Barthes’s semiotics methods, Slavoj Zizek’s fantasy and
emancipation concept, and George Ritzer’s holocaust dimension theory of fast
food restaurant. These prominent figures are intentionally defined as the
visual-foodgasm phenomena and the
tasteful-foodgasm phenomena are in
the different fields, hence require different perspectives and theories to
identify.
Keywords; foodgasm, fantasy, emancipation
Abstrak
Tulisan terkait berupaya mengkaji hadir dan merebaknya fenomena foodgasm dewasa ini beserta berbagai
implikasi sosial yang dibawanya. Secara sederhana, foodgasm dapat diartikan sebagai; “sensasi menyenangkan saat makan”.
Sensasi tersebut sesungguhnya tak sekedar menjamah aspek “rasa” atau pencecap
manusia, melainkan pula aspek visual. Dalam hal ini, fantasi menjadi ihwal
penting yang bermain di keduanya. Lebih jauh, pengkajian ini berupaya pula merumuskan
alternatif-alternatif emansipasi (pembebasan) atas fantasi, di antaranya
melalui perspektif “kecabulan” Jean Baudrillard, metode semiotika Roland
Barthes, konsep fantasi dan emansipasi Slavoj Zizek, serta tak ketinggalan
pemikiran George Ritzer tentang dimensi holocaust
dalam restoran cepat saji. Berbagai tokoh dengan beragam perspektif tersebut
sengaja disertakan mengingat fenomena foodgasm-visual
dan foodgasm-rasa berada pada dua ranah
yang berlainan, dan menuntut perspektif berikut teori yang berbeda pula dalam
mengkajinya.
Kata kunci; foodgasm, fantasi, emansipasi
“We have to eat; we like to eat; eating make us feel good; it is more
important than sex.”
[Robin Fox, Food & Eating]
Pendahuluan: Dari McDonaldisasi Masyarakat
hingga Foodgasm
Dalam beberapa dekade terakhir, baik makanan (food) ataupun “cara makan” (eating)
menjadi perhatian banyak pakar ilmu sosial di berbagai belahan dunia. Semisal,
munculnya kajian Globalising Food
(1997) dari David Goodman dan Michael J. Watts, kemudian Fast Food Nation (2002) karya Eric Schlosser, tak ketinggalan Geoff
Andrews dengan The Slow Food Story
(2008), dan masih banyak lagi. Namun, dari serangkai nama tokoh-tokoh tersebut,
kiranya terdapat seorang tokoh gaek yang
tak asing lagi membincang dimensi sosial makanan dan terkenal lewat kajiannya
tentang “McDonaldisasi masyarakat” (McDonaldization
of society), yaitu George Ritzer. Melalui kajiannya, Ritzer (2005: 565) tak
sekedar menunjukkan nilai material dari sebuah makanan, tetapi juga bagaimana
sebuah makanan sekaligus “cara memakannya” merepresentasi jejaring sistem
sosial-kultural yang tengah berlangsung di masyarakat, bahkan dunia.
Pasca dipopulerkan Ritzer, kajian seputar dimensi sosial-humaniora makanan
pun kian marak. Di samping ketiga tokoh yang telah disebut sebelumnya, terdapat
pula analisis antropologis Robin Fox (2002: 1) yang melihat makanan sebagai
simbol hospitality ‘keramah-tamahan’
serta kental dengan muatan altruisme sosial, yakni bagaimana makanan kerap dibagikan
secara cuma-cuma dan disantap secara kolektif sehingga menumbuhkan rasa
kebersamaan. Analisis Stewart R. Clegg (1996: 147, 150-151) mengenai bagguette (roti Perancis) juga tak kalah
genit, ia mengaitkan bagguette dengan
gejala posmodernisme di mana timbul kejenuhan masyarakat Barat akan
standarisasi produk pangan modern, sehingga berbagai industri kecil pembuatan bagguette yang masih mempertahankan
cara-cara lama; ukuran yang tak terstandar, kemasan yang biasa, serta roti yang
tak tahan lama;
justru mampu bertahan dibanding perusahaan-perusahaan bagguette modern dengan kualitas jauh lebih baik.
Masih di ranah posmodernisme, dewasa ini muncul fenomena yang sering
disebut sebagai “foodgasm”. Istilah tersebut berasal dari dua kata; yakni food ‘makanan’, dan orgasm ‘orgasme’. Pengertian “orgasme” di sini sebagaimana pengertiannya
di ranah seksualitas: puncak kenikmatan atau kepuasan dalam hubungan seks;
hanya saja, kulminasi kenikmatan tersebut berada di ranah konsumsi, yakni
makanan. Secara sederhana, foodgasm
sendiri dapat diartikan sebagai, “A
pleasurable sensation from eating food” [“Sensasi yang menyenangkan dari (saat)
memakan makanan”] (Neale, 2005: 170; Wilson, 2006: 350). Sensasi
tersebut dianggap tak ubahnya sensasi orgasme saat berhubungan seks. Namun
demikian, pendefinisian ini dirasa masih sangat terbatas mengingat foodgasm turut bermain di ranah citra
atau gambar. Dengan kata lain, sebelum ia menjamah indera pencecap, terlebih
dahulu ia “bermain” di ranah visual; merekayasa ataupun memanipulasi
penglihatan sehingga memaksa untuk mengonsumsinya. Serangkaian hal tersebutlah
yang kiranya menarik dikaji lebih jauh dalam pembahasan ini, mengingat: pertama, masih begitu prematurnya pendefinisian
tentang foodgasm sehingga dirasa
kurang mampu merepresentasi fenomena terkait; dan kedua, masih jarangnya pembahasan seputar foodgasm dalam kerangka kajian sosial-humaniora yang cukup
sistematis di tanah air.
“Kreativitas yang Diotomatiskan”: Pemroduksi
Fantasi tanpa Batas
Istilah “kreativitas yang diotomatiskan”
digunakan Robert Pepperell (2009: 203-204) guna menunjuk pada hadirnya era posthuman ‘pascamanusia’. Apa yang
dimaksudkannya adalah, bila dahulu teknologi diciptakan manusia dan berstrata
di bawahnya, maka kini teknologi bertempat sejajar dengan manusia, bahkan
melampauinya. Ini mengingat, begitu akutnya ketergantungan manusia akan
teknologi dewasa ini. Sebagai misal, kita tak dapat membayangkan hidup seminggu
tanpa telepon genggam; seberapa banyak relasi bisnis kita akan hilang, seberapa
besar kerugian finansial yang bakal diderita; dan akhirnya, seberapa kacau
hidup kita dibuat tanpanya. Bagi Pepperell, superioritas teknologi atas manusia
inilah yang kemudian turut menyebabkan bergesernya pemaknaan akan “kreativitas”.
Apabila dahulu kreativitas ajeg
diterjemahkan sebagai hasil cipta-manual tangan manusia yang kreatif, namun
kini, kita telah terbiasa menggunakan beragam aplikasi teknologi guna
menghasilkannya, semisal melalui; adobe
photoshop, corel draw, atau microsoft office picture manager.
Alhasil, kreativitas yang dihasilkan pun tak lagi murni berasal dari tangan
manusia, melainkan teknologi. Pertanyaannya, masihkah hal yang demikian disebut
sebagai kreativitas.
Terkait hal di atas, Jean
Baudrillard (1988: 171-172) berkomentar ihwal betapa akutnya kehidupan
simulatif berikut artifisial (buatan) yang mendera masyarakat kontemporer. Bagi
Baudrillard, hal tersebut tak lain disebabkan oleh “simulakra”, yakni instrumen
pengonversi hal-hal konkret pada abstrak, dan begitu pula sebaliknya: beragam hal
abstrak pada konkret. Contoh sederhana simulakra dalam pengkajian ini adalah
komputer. Melalui beragam
software di dalamnya, kita dapat membuat
suatu citra yang awalnya biasa menjadi luar biasa, tak mungkin menjadi mungkin,
pun tak menarik menjadi menarik. Sebagai misal, kita bisa menambahkan sayap
pada foto manusia; atau seperti kerap kita saksikan dalam film-film hollywood,
industri perfilman di sana nyaris, atau bahkan telah mampu mewujudkan beragam
fantasi manusia ke dalam film, semisal Alice
in Wonderland, Transformers, Avatar, Spiderman, dan lain sejenisnya.
Simulakra tersebutlah yang didaulat Baudrillard (1988: 166-167) menjadi
biang munculnya “hiperealitas”, yakni hal-hal yang melampaui kenyataan; atau
dapat pula: kenyataan baru yang melampaui kenyataan sebelumnya. Inilah mengapa,
tak sedikit audiens yang terpengaruh dan bersikeras hendak menjadi tokoh yang
disaksikannya dalam film. Bagi dunia advertising,
simulakra sengaja digunakan untuk memberi “efek” pada suatu produk, mungkin
dengan harapan merepresentasi produk seperti yang dikehendaki produsen. Citra
yang dihasilkan simulakra tampak dilebih-lebihkan, dengan maksud memberi kesan pada
konsumen agar mencoba atau mencicipi. Bagi Baudrillard, “kecabulan” pun tak
terhindarkan sebagai dampak-ikutan kemudian, tak terkecuali pada citra-citra
simulasi makanan.
Foodgasm sebagai Kecabulan
Istilah foodgasm dalam subbab ini menunjuk pada citra atau gambar makanan
yang membuat mereka terpana melihatnya, pun tak jarang pula meneteskan air
liur. Dengan demikian, pengkajian foodgasm
sebagai citra lebih berkutat pada persoalan kode, simbol, serta ikon yang dipermainkan
untuk memanipulasi penglihatan, serangkaian hal tersebutlah yang menggiring
pada kecabulan. Dalam konteks ini, citra cabul atau kecabulan tak selalu berkenaan
dengan pornografi atau pornoaksi, melainkan segala sesuatu yang “menggoda” dan “mengusik”
(Baudrillard, 2006: 21-23, 49-50). Memang, ihwal termudah memisalkannya dengan pornografi;
kecabulan yang melekat sesungguhnya tak ditemui pada citra-citra manusia
telanjang (baca: vulgar), melainkan pada citra yang bersifat “semi”. Sebagian dari
citra tertutup tersebutlah yang begitu mengusik dan menggoda—seperti apa wujudnya?—meskipun ia takkan
pernah benar-benar diketahui. Namun sesungguhnya, di sinilah fungsi utama dari
kode yang disembunyikan, yakni untuk terus “menjaga minat” atau antusiasme. Persoalan
menjadi lain ketika segalanya telah terungkap, maka tak ada lagi yang menarik karena
tak ada teka-teki untuk dipecahkan.
Begitu pula dengan banner atau spanduk yang memuat citra
makanan di pinggiran jalan, ambilah misal sebuah banner besar bergambarkan burger; ia sesungguhnya cabul karena
mengusik dan menggoda mereka yang melihatnya. Instrumen simulakra membuatnya seakan
sedap disantap; degradasi yang digunakan untuk “menyangatkan” warna kulit roti,
arah cahaya yang dibelokkan untuk membuat bagian pinggir daging tampak
mengkilap, kecerahan keju dan selada yang dilebih-lebihkan agar tampak segar,
serta mayones yang dibuat tampak lumer guna mengesankan kehangatannya di pencecap,
juga memberi pesan bahwa ia tak boleh dibiarkan berlama-lama—sarat segera
disantap. Tak lupa, sudut pengambilan gambar dari bawah ke atas sengaja digunakan
untuk mengesankannya tampak besar, mewah, angkuh, serta prestis jika dapat dimiliki.
Secara keseluruhan, kode yang berupaya dibangun adalah keidealan makanan ini
dengan komposisi gizi seimbang antara hewani maupun nabati, atau setidaknya,
memenuhi keduanya. Ikon yang tercetus kemudian pun menyirat burger tersebut
sebagai makanan praktis, enak, mengenyangkan, dan menyehatkan.
Ekses dari serangkaian kodifikasi di
atas adalah terpicunya fantasi untuk mencicipi. Sebagaimana diutarakan
Baudrillard (2006: 51), “Godaan justru
datang dari tanda-tanda yang kosong, samar, mentok, ngawur, dan kebetulan
belaka; yang menggelincir dengan lancar sehingga mengubah indeks pembiasan
ruang”. Apa yang dimaksudkannya adalah, citra burger di atas memang tak
menyertakan teks guna menunjukkan berbagai pseudo kualitasnya secara eksplisit,
melainkan secara samar; dan memang, demikianlah prinsip simbol: memuat
informasi yang sangat sedikit (Berger, 2010: 19). Namun kiranya, melalui berbagai
kode acak yang ditampilkannya—citra roti pembungkus, daging, keju, selada, dan lain
sebagainya—ia telah secara jelas menuntun pikiran serta imajinasi audiens:
bahwa cukup dengan melihatnya, seolah mereka telah memahami sensasinya. Pun, mengingat keberadaannya di ruang
publik, maka ia dapat dijuluk sebagai “perkosaan visual”; sebentuk paksaan
untuk terus berfantasi atasnya.
Membongkar Kecabulan: Semiotika dan Perlintasan
Fantasi
Tentu, upaya tersahih guna membongkar
beragam kodifikasi citra simulatif dapat dilakukan melalui analisis semiotika
atau semiologi. Dalam hal ini, metode semiotika Roland Barthes yang memuat keberadaan
lapisan semiotika tingkat pertama dan kedua dirasa cukup memadai. Dalam
semiotika lapis pertama, ditemui citra sebagaimana adanya; bahwa citra tersebut
adalah burger dengan berbagai bahan (komposisi) yang menyusunnya. Dengan kata
lain, didapatkan “denotasi” dari citra tersebut. Selanjutnya, pada lapis kedua,
sejumput pertanyaan mulai menyerua lewat pengamatan lebih seksama: mengapa tak
ditemui obyek lain selain burger tersebut; tisu mungkin, asbak, atau yang
lainnya; apakah ia berada dalam ruang hampa?. Mengapa ia tak dibungkus, atau berada
dalam genggaman? Mengapa pilihan latar yang digunakan demikian? Bukan berlatar
buku-buku, atau dapur tempat ia dibuat? Pun
beragam pertanyaan lainnya. Bagi Barthes
(dalam Sunardi, 2002: 104-105), ketika audiens telah menjamah semiotika lapis
kedua, maka ia telah mencapai “mitos”.
Mitos dalam sudut pandang Barthes
(2009: 151-153) bukanlah mitos-mitos layaknya di era Yunani Kuno, melainkan sistem
komunikasi yang mewujud sebagai “pesan” baik secara tertulis maupun
representatif—citra, simbol, reportase, dan lain-lain, serta memiliki caranya
sendiri untuk mengutarakan pesannya. Tegas dan jelasnya, ia merupakan “cara
penandaan” atas sesuatu, dan sejauh segala sesuatu tersebut memuat wacana, maka
ia mengandung mitos. Kiranya, mitos dalam citra burger terkait terjawab lewat
serangkai pertanyaan di atas. Ia—burger—tak disandingkan dengan obyek-obyek
lain karena dikhawatirkan bakal mengacau fokus. Begitu pula, ia tak terbungkus
karena justru akan menyensor seluruh kode, adapun citranya yang bebas-apung
bertujuan menciptakan kesan higienis; apabila ia telah tersentuh tangan, maka
kesan tersebut sedikit-banyak akan hilang; dan beragam tafsir semiotik lainnya.
Agaknya, contoh mitos termudah dapat dimisalkan lewat kemasan mie instan yang kerap
ditemui di keseharian. Kemasan tersebut menambahkan kode-kode serta kategori guna
merepresentasi varian citarasa yang ditawarkan, semisal; citra potongan daging ayam,
belahan telur, potongan tomat, seledri, dan lain sebagainya; namun senyatanya,
berbagai kategori tersebut tak pernah ditemui di dalamnya. Dengan demikian, ia hanyalah
simbol berikut wacana kosong dan menemui bentuknya sebagai mitos.
Di ranah berlainan, Slavoj Zizek turut
menawarkan solusi bagi subyek guna melepaskan diri dari fantasi. Mengamini Jacques
Lacan, Zizek (2007: 40) menyatakan prinsip fantasi sebagai “Che voi?” [“Apa yang kau
inginkan dariku?”]. Baginya, fantasi selalu berupaya mengatasi jarak antara
subyek dengan realitas, dalam konteks ini, subyek dengan eksistensi burger
secara konkret. Fantasi sengaja disuntikkan guna “menjaga minat” subyek, ini
mengingat, ketika subyek dengan obyek fantasi tak berjarak, maka keinginan pun
akan sirna. Dapatlah ditilik bagaimana kerja fantasi citra burger untuk terus
menjaga animo dan menuntun subyek hingga mengonsumsinya. Inilah mengapa, Zizek
turut mendaulat fantasi sebagai cara subyek mengatur jouissance ‘kenikmatan’-nya. Bagi Zizek (2008: 141), upaya guna
melakukan emansipasi atasnya dapat dilakukan dengan traversing the fantasy ‘melintasi fantasi’. “…only ‘traversed’: all we have to do is experience how there is
nothing ‘behind’ it” [“…hanya dengan ‘melintasinya’ (fantasi): kita akan
mendapati pengalaman bahwa tak ada apapun ‘di balik’ itu (fantasi)”], tegas
Zizek.
Ia—Zizek (1992: 5-6)—memisalkannya secara sederhana dengan “surat yang
selalu sampai ke tujuan”. Faktual, terdapat “perbedaan rasa” ketika kita tengah
menanti-nantikan surat tersebut dibanding saat kita telah memegang atau membacanya.
Dalam konteks foodgasm, emansipasi
melalui traversing the fantasy dapat
termanifestasi lewat serangkai pertanyaan kritis sebagai berikut; Apakah
kenikmatan saat memandang makanan tersebut tak ubahnya saat memakannya? Mungkinkah
makanan yang tersaji sama persis dengan yang kita saksikan? Benarkah
visualisasi makanan tersebut betul-betul menjamin dan merepresentasi kenikmatannya?
Adakah rasa kenyang yang berbeda setelah kita menyantapnya dibanding dengan makanan
lainnya?. Dengan kata lain, Zizek mengajak subyek untuk “seakan pernah
mengalami” layaknya kasus “surat yang selalu sampai ke tujuan”; dengan demikian,
fantasi pun terlampaui.
Jalan Lain Emansipasi:
Menakar Foodgasm sebagai “Holocaust” Gaya Baru
Apabila pada subbab sebelumnya
pengkajian foodgasm berfokus pada wujudnya
sebagai citra, maka subbab ini berfokus pada manifestasinya sebagai taste atau “rasa”. Sempat disinggung di
muka betapa dewasa ini rumah makan cepat saji, atau apa yang diistilahkan
Ritzer sebagai “McDonaldisasi masyarakat” tampak menggejala secara akut. Bagi
Ritzer, mengguritanya restoran tersebut disebabkan oleh kesesuaiannya dengan
jiwa zaman, apabila dahulu modernitas atau modernisasi selalu dikaitkan dengan
birokrasi, maka kini ia adalah restoran cepat saji. Memang, restoran cepat saji
memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam masyarakat modern, namun
Ritzer menengarai adanya berbagai problem akut yang menyertainya. Mengadopsi
pemikiran Zygmunt Bauman ihwal holocaust-Nazi sebagai produk paripurna
modernitas, Ritzer (2005: 564-577) mengadaptasikannya pada fenomena McDonalds yang
merebak di berbagai belahan dunia. Lebih jelasnya, perhatikan tabel
perbandingan antara holocaust-Nazi dengan McDonalds di bawah ini.
|
Holocaust-Nazi
|
|
McDonalds
|
1.
|
Rasionalitas formal
Birokrasi sebagai alat. Birokrasi adalah
organisasi yang dibentuk negara untuk melancarkan fungsi negara, salah satu
karakternya ialah “rasionalitas
dengan spesialisasi”, bertujuan untuk mencapai efisiensi tingkat tinggi.
|
|
Rasionalitas formal
Memberikan pesanan melalui jendela pada konsumen
adalah cara paling cepat mencapai tujuan bagi kedua
belah pihak. Pelayan mendapatkan uang dengan cepat, begitu pula dengan konsumen: mendapat pesanan dengan cepat.
|
2.
|
Efisiensi
Penggunaan gas lebih efisien untuk membunuh
manusia ketimbang peluru. Melalui kalkulasi, seberapa banyak yang dapat
dibunuh berbanding seberapa pendek waktu yang untuk melakukannya.
|
|
Efisiensi
Seberapa banyak pesanan yang dapat
keluar, dan seberapa pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan
pesanan tersebut.
|
3.
|
Prediktabilitas
Kamp konsentrasi di berbagai negara
didesain serupa.
|
|
Prediktabilitas
McDonalds Amerika Serikat didesain
serupa dengan McDonalds
di berbagai belahan dunia.
|
4.
|
Teknologi nonmanusia
Kekuasaan dan
peraturan-peraturan dalam kamp konsentrasi berdampak pada dehumanisasi.
|
|
Teknologi nonmanusia
Menggunakan koki yang tidak trampil, sekedar
mengikuti petunjuk rinci dan metode garis peracikan yang
ditetapkan dalam memasak dan menyajikan; berdampak
pada dehumanisasi cara makan/makanan.
|
5.
|
Hanya berurusan pada dampak finansial
dari tindakan yang
dilakukan
Penggunaan gerbong oleh Nazi dengan
menganggap manusia-manusia sebagai “angka”,
yakni membiarkan mereka berdesak-desakan, dehidrasi dan
menderita—perihal terpenting adalah membawa muatan
sebanyak-banyaknya dengan biaya termurah, cepat dan aman.
|
|
Hanya berurusan pada dampak finansial
dari tindakan mereka
Penggunaan stereoform ‘gabus’
dalam penyajian makanan agar murah faktual menyebabkan penyakit kanker. McDonald’s menuai protes konsumen vegetarian
karena lebih dari sepuluh tahun berbohong tak menggunakan
lemak nabati untuk menggoreng kentang iris, melainkan lemak
sapi.
|
6.
|
Pekerja yang tak digaji
Yahudi bekerja dalam pabrik-pabrik tanpa menerima
upah.
Dalam sistem, Yahudi dipaksa melepaskan
pakaiannya sendiri, masuk ke kamp gas sendiri, Yahudi-Yahudi yang
masih tersisa diperintahkan untuk membersihkan mayat
saudaranya sendiri (membawanya ke tungku pembakaran).
Tubuh mereka juga digunakan sebagai bahan membuat
sabun, kain, dll. (tidak ada yang tersisa).
|
|
Pelanggan menjadi pekerja yang tak digaji
Pelanggan McDonalds membumbui makanannya sendiri, serta
membersihkan kotorannya sendiri (terlebih jika pesanan tak
dimakan di tempat).
|
Melalui kolom “teknologi nonmanusia”
di atas, dapatlah ditilik betapa foodgasm-rasa
yang dihadirkan restoran cepat saji tak lain sekedar prosedur teknis semata, yakni telah
ditemuinya takaran serta racikan baku untuk memasak beragam menu yang ditawarkan.
Ritzer mengistilahkannya sebagai “dehumanisasi cara makan” mengingat tak
ditemuinya perbedaan antara bagaimana peternak memberi makan hewan-hewan
ternaknya dengan bagaimana proses dan cara McDonalds menyajikan makanan bagi para
pelanggannya. Patut disayangkan, dewasa ini tak sedikit rumah makan tanah air
yang justru mengadopsi sistem dan cara kerja restoran cepat saji Barat; baik
rumah makan lokal yang sengaja me-McDonaldisasi-kan dirinya, ataupun rumah
makan lokal pada umumnya. Orientasi foodgasm
yang berupaya mereka sajikan pada setiap pelanggan melalui pembakuan proses pengolahan
makanan, tanpa disadari justru berdampak pada dehumanisasi cara makan berikut eksploitasi
dimensi “rasa” manusia.
Dapatlah dikatakan, pengalaman foodgasm
dengan sengaja mematikan sensibilitas indera pencecap untuk selalu mencapai
ektase, dan ini tak ubahnya kecabulan. Sebagaimana diutarakan Baudrillard
(2006: 14), “Ekstase adalah kondisi di
mana seluruh fungsi diciutkan dalam satu dimensi… Seluruh peristiwa, ruang, dan
ingatan dimampatkan dalam dimensi tunggal ‘informasi’,
dan inilah kecabulan”. Parahnya, demi mewujudkan sensasi aktivitas makan
sekaligus menjadikannya candu, para produsen foodgasm cepat saji seolah menutup mata dari penggunaan bahan-bahan
kimia berbahaya bagi kesehatan (Schlosser, 2002: 15, 91). Pada akhirnya, vis-à-vis antara kenikmatan aktivitas makan
dengan dimensi kemanusiaan pun sarat dikalkulasikan kembali.
Kesimpulan dan Penutup
Melalui berbagai uraian yang telah
disampaikan sebelumnya, kiranya telah dipaparkan secara jelas tentang bagaimana
fantasi bermain dalam foodgasm. Secara
visual, kehadirannya tak terlepas dari kode yang disimulasikan secara apik sehingga
melahirkan hiperealitas yang mengusik dan menggoda. Di satu sisi, perwujudannya
di ranah taste ‘rasa’ faktual sekedar
menemui bentuknya sebagai prosedur teknis yang bernegasi dengan nilai-nilai
konsumsi kemanusiaan. Tak pelak, kedua persoalan tersebut menuntut alternatif
emansipasi yang berbeda bagi setiapnya. Metode semiotika Roland Barthes dan perlintasan
fantasi Slavoj Zizek agaknya telah berhasil membongkar kepalsuan fantasi foodgasm-visual. Di sisi lain, problem foodgasm-rasa kiranya terjawab melalui
pengalkulasian kembali besaran resiko yang ditimbulkan foodgasm atas kemanusiaan. Terminus “kemanusiaan” sebagaimana
dimaksudkan di sini tidaklah sekedar menjamah dimensi humanisme yang bersifat filosofis
lagi abstrak, melainkan pula wujudnya secara konkret, yakni kesehatan dan
keamanan manusia. Kini, persoalan yang tertinggal hanyalah mengomunikasikan
berbagai temuan di atas kepada awam secara mudah.
*****
Referensi
Barthes, Roland, 2009,
Mitologi, Kreasi Wacana.
Baudrillard, Jean,
2006, Ekstasi Komunikasi, Kreasi
Wacana.
Baudrillard, Jean,
1998, Simulacra and Simulations,
Stanford University Press.
Berger, Arthur Asa,
2010, Semiotika: Tanda-tanda dalam
Kebudayaan Kontemporer, Tiara Wacana.
Clegg, Stewart R., 1996,
Roti Perancis, Fashion Italia dan Bisnis
Asia, Kreasi Wacana.
Fox, Robin, 2002, Food & Eating: An Anthropological
Perspective, Oxford University Press.
Neale, Naomi, 2005, The Mile-High Hair Club, Books in
Motion.
Pepperell, Robert,
2009, Posthuman: Kompleksitas Kesadaran,
Manusia dan Teknologi, Kreasi Wacana.
Ritzer, George &
Douglas J. Goodman, 2005, Teori Sosiologi
Modern, Kencana.
Schlosser, Eric, 2002,
Fast Food Nation, Penguin Books.
Sunardi, ST., 2002, Semiotika Negativa, Kanal.
Wilson, Elisabeth,
2006, Goddes: Be the Woman You Want to Be,
Infinite Ideas.
Zizek, Slavoj, 1992, Enjoy Your Symptom!, Routledge.
Zizek, Slavoj, 2007, How to Read Lacan, WW Norton &
Company.
Zizek, Slavoj, 2008, The Sublime Object of Ideology, Verso.
Tentang Penulis
Wahyu Budi Nugroho. Merupakan staf pengajar pada Prodi Sosiologi,
Fisip-Udayana. Memiliki minat studi pada tema seputar pengkajian aktor dan
agensi sosial. Tulisannya telah tersebar di berbagai media cetak dan elektronik
lokal maupun nasional, serta berbagai jurnal ilmiah. Beberapa buku yang telah
ditulisnya antara lain; Koruptorrajim:
Surat-surat Cinta untuk KPK (bersama Edi Akhiles, dkk., IRCiSoD, 2012), Orang Lain adalah Neraka: Sosiologi
Eksistensialisme Jean Paul Sartre (Pustaka Pelajar, 2013), Alienasi, Fenomenologi, dan Pembebasan
Individu (bersama Dr. M. Supraja, LOGIS, 2013), Menuju Teknologi Transkomunitas (bersama Dr. M. Supraja, LOGIS
2014), serta buku seri kuliah lapangan Teknologi
Tepat Guna yang Berpihak pada Penguatan Kesejahteraan Masyarakat (LPPM-UGM,
2014). Hingga kini aktif menuangkan ide-idenya di http://kolomsosiologi.blogspot.com/.

 05.39
05.39
 Wbn
Wbn